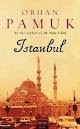Pernah nggak dengar omongan seperti ini? [Setting: jalanan Jakarta yang macet dengan mobil-mobil yang mengantri panjang. Tiba-tiba sebuah mobil nekat menyeruak barisan dan berjalan di sisi kanan sampai kemudian bertemu dengan mobil lain dari arah yang berlawanan. Si mobil nekat pun mepet ke kiri berusaha memasuki barisan, tapi tak ada yang mau member ruang, sehingga jalanan pun makin macet] “Dasar orang Indonesia, nggak bisa diajak tertib! Coba di Barat, nggak ada situasi kayak gini. Malah macet pun mungkin nggak ada. Huh, namanya aja Indonesia! Kapan mau maju ini bangsa kalau orang-orangnya model begini semua?"
Pernah nggak dengar omongan seperti ini? [Setting: jalanan Jakarta yang macet dengan mobil-mobil yang mengantri panjang. Tiba-tiba sebuah mobil nekat menyeruak barisan dan berjalan di sisi kanan sampai kemudian bertemu dengan mobil lain dari arah yang berlawanan. Si mobil nekat pun mepet ke kiri berusaha memasuki barisan, tapi tak ada yang mau member ruang, sehingga jalanan pun makin macet] “Dasar orang Indonesia, nggak bisa diajak tertib! Coba di Barat, nggak ada situasi kayak gini. Malah macet pun mungkin nggak ada. Huh, namanya aja Indonesia! Kapan mau maju ini bangsa kalau orang-orangnya model begini semua?"Dan kita-kita yang kebetulan mendengar celetukan seperti itu pun manggut-manggut, seolah ikut menyesali, kenapa kita mesti dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kenapa nggak jadi orang ‘Barat’ (baca: bule) saja yang selama ini identik dengan orang-orangnya yang maju dan beradab?.
Tapi coba deh baca bukunya Agustinus Wibowo yang berjudul “Selimut Debu”, dijamin kita akan mensyukuri terlahir sebagai orang Indonesia, dengan negaranya yang (relatif) damai, alamnya yang indah, hasil buminya yang berlimpah, para pemimpin yang cukup mengerti bagaimana menjalankan perannya. Ya, soalnya buku yang tebalnya hampir 500 halaman ini bercerita tentang sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya berselimut debu, dengan lalat yang berterbangan di hampir setiap sudut negara, tak putus dirundung konflik dan persoalanan keamanan, perekonomian yang tidak berprospek, serta hasil bumi andalannya adalah opium. Itulah Afganistan.
Dari awal sampai akhir membaca buku itu, saya tidak habis pikir, kenapa si Agustinus ini tertarik untuk datang ke negara yang dari dulu cuma terkenal tentang berita perangnya saja? Apa menariknya negara yang identik dengan ‘pusat pelatihan’ para teroris di Indonesia itu? Yang ada malah bertaruh nyawa. Mending ke Swiss kek, Perancis kek, pokoknya ‘Barat’ lah!
Tapi kalau kita pernah mengikuti serial petualangannya Agustinus Wibowo di Kompas online (sekarang sudah nggak ada, dia udah punya blog sendiri) yang judulnya diantaranya: “Mengembara ke Negeri-negeri Stan” (maksudnya bekas wilayah bagian Uni Soviet yang nama negaranya berakhiran ‘stan’ kayak Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgistan, Kazakhstan, dll, dsb, dst), kita jadi memahami, bahwa buat Agustinus, semakin nggak populer sebuah negara sebagai tujuan wisata dunia, semakin tertarik dan tertantang dia untuk mengunjunginya bukan sebagai turis, tapi pengelana. Dan Agustinus bukan seorang backpacker biasa, he’s an explorer, an adventurer!
Ini, saya kutipkan kalimat dari buku yang menceritakan awal mula ketertarikan si Agustinus untuk menjelajahi Afganistan (to prove that he’s not completely sane!) yang katanya terinisasi oleh seorang penjelajah asal Jepang yang dikenalnya dalam sebuah perjalanan.
“Lelaki Jepang ini sudah berkelana ke pelbagai penjuru Afganistan…Semuanya dengan mencegat kendaraan di jalan. Tak pernah dia tinggal di penginapan, selalu di kedai teh, yang konon selalu menyediakan tempat bermalam gratis bagi siapa pun yang makan di sana…Karpetnya jorok. Lalatnya ratusan, berdenging-denging ribut…Belum lagi kalau harus dipaksa makan di sini hanya demi menginap gratis…Daging kambing yang seharusnya merah segar semua tampak hitam dikerubungi lalat. Selain debu, makanan itulah yang menjadi santapan sehari-hari di negeri ini” (hal. 13).
Ada yang menganggap ini menarik? Ayo tunjuk tangan! Kalau merasa diri normal, pasti sepakat kalau saya berikan komentar singkat tentang keterangan ini: amit-amit! Tapi coba, apa komentar Agustinus tentang ini:
“Berkeliling Afganistan dengan menumpang truk, menginap gratis di kedai teh kumuh, berkawan dengan dengungan lalat gemuk, mengunjungi dusun terpencil di balik gunung, mencari Firdaus yang tersembunyi, semuanya tiba-tiba menjadi mimpi saya di malam-malam berikutnya” (hal. 14).
See what I mean? Tapi itulah keistimewaan seorang Agustinus Wibowo. Hanya berbekal 300 dollar AS (kurang dari 3 juta rupiah) dia pun memulai petualangannya ke Afganistan di tahun 2006. Bekal yang tak seberapa itu pun dicuri orang saat dia sedang beristirahat. Dan dengan sisa 5 dollar AS (kurang dari 50 ribu rupiah), dia berusaha melanjutkan perjalanan (yang makin berat tentu saja) dan mencari pertolongan dari seorang teman.
Ini masih belum seberapa lho. Dia juga sering terserang diare (tapi tidak selalu menemukan toilet yang layak), dirayu homo (yang memang marak di negara yang ketat melarang hubungan lawan jenis di luar lembaga pernikahan, jadi buat amannya mereka memilih hubungan sejenis!), dan ditipu oleh penduduk setempat yang mengambil kesempatan dari ketidaktahuannya.
Semua itu bagi Agustinus terbayar saat dia menyaksikan keindahan Koridor Wakhan, eksotisme Chapursan, dan wilayah-wilayah lain yang tersembunyi dan terlupakan. Waktu seakan berhenti di sana. Para penduduknya hidup dengan teknologi yang masih sangat sederhana. Ada foto-foto tempat-tempat tersebut yang disisipkan oleh Agustinus dalam bukunya. Memang terlihat indah (dari foto lho!).
Lebih istimewa lagi, Agustinus selalu menyisipkan pengetahuan menarik saat dia menceritakan perjalanannya. Fakta politik, sosial, maupun budaya Afganistan, selalu disisipkan tanpa terkesan menggurui. Tentang pemerintahannya yang tidak efektif sehingga di suatu daerah setiap orang bisa membawa senjata api kemana-mana, kayak orang bawa golok kalau di Indonesia. Tentang Bank Dunia dan lembaga-lembaga internasional lain dengan program-program pembangunannya yang sama tidak efektifnya tapi menggaji stafnya hingga ribuan dollar per bulan. Tentang komunitas orang cacat korban ranjau yang kalau dikumpulkan dan didanai bisa bikin parpol sendiri di sana. Tentang pembenaran mengapa kebanyakan para wanita di sana memilih untuk terus mengenakan burqa, meskipun era Taliban telah lewat. Tentang etnis Pashtun yang merasa diri paling superior dihadapan etnis di Afganistan lainnya karena lekat dengan sejarah tokoh-tokoh besar.
Semua ini bagi kita akan sama asingnya dengan kehidupan yang ada di Saturnus kalau tidak ada orang dengan nyali sebesar Agustinus. Dan tanpa mengetahui ini semua, sebagian kita juga tidak akan pernah mensyukuri terlahir sebagai bangsa Indonesia, yang meski sering nggak tertib, tapi masih jauh lebih banyak memiliki hal yang bisa dinikmati daripada para penduduk negara berselimut debu (dan lalat) itu. Hidup Indonesia!
DN