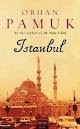Siapa bilang hanya karya ilmiah yang membutuhkan data dan referensi? Sebuah tulisan fiksi pun idealnya memiliki rujukan data dan referensi saat menyajikan latar belakang atau setting ceritanya. Apalagi kalau latar belakang atau setting cerita itu real bukan semacam dongeng. Meskipun fiksi itu dimaksudkan semata-mata menghibur, namun alangkah baiknya apabila para pembacanya tidak sekedar diberi refreshment tapi juga dijanjikan potongan-potongan pengetahuan untuk memperkaya wawasan dan khasanah pemikiran. Minimal, janganlah para pembaca ‘dibodohi’ dengan penjelasan yang apa adanya, apalagi fakta yang diselewengkan.
Siapa bilang hanya karya ilmiah yang membutuhkan data dan referensi? Sebuah tulisan fiksi pun idealnya memiliki rujukan data dan referensi saat menyajikan latar belakang atau setting ceritanya. Apalagi kalau latar belakang atau setting cerita itu real bukan semacam dongeng. Meskipun fiksi itu dimaksudkan semata-mata menghibur, namun alangkah baiknya apabila para pembacanya tidak sekedar diberi refreshment tapi juga dijanjikan potongan-potongan pengetahuan untuk memperkaya wawasan dan khasanah pemikiran. Minimal, janganlah para pembaca ‘dibodohi’ dengan penjelasan yang apa adanya, apalagi fakta yang diselewengkan.That’s why saya sangat salut kepada para penulis fiksi yang benar-benar mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran dalam menciptakan karya-karya mereka. Tidak semata-mata menulis (atau mengetik) apa yang ada di kepala mereka, tapi berusaha ‘mempertanggungjawabkan’ logika bercerita yang sedang mereka bangun dengan data dan referensi yang diupayakan akurat. Eiji Yoshikawa dan Pramudya Ananta Toer mengolah cerita-cerita mereka dengan setting sejarah jaman-jaman kerajaan yang detail. Karl May yang orang Jerman berhasil menciptakan setting Amerika Serikat yang cukup detail buat tokoh Old Shatterhand di serial Winetou-nya. Padahal konon waktu dia menuliskan buku itu sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di bumi Amerika. Jadi hanya berbekal referensi tentang negara tersebut. Lalu Dewi 'Dee' Lestari bahkan sengaja mempelajari buku-buku science populer (padahal background-nya ilmu sosial) demi tercipta novel Supernova yang menggunakan konteks science. Masih ada Agatha Christie yang apabila sedang menggarap babak pembunuhan yang menggunakan racun, dia pun rajin mengumpulkan info tentang jenis-jenis racun berikut tingkat dosis yang mematikan dan reaksinya kepada sang korban. Tidak jarang Ibu Agatha berkonsultasi pada kalangan medis mengenai hal ini.
Jadi semuanya tidak asal ngecap atau asal tempel. Meskipun mungkin ada beberapa data yang tidak benar-benar tepat, tapi paling tidak usaha mereka patut dihargai tinggi. Apalagi di tengah keterbatasan akses terhadap informasi, seperti Pramudya saat menuliskan “Arok Dedes”, misalnya. Saya tidak bisa membayangkan darimana dia mengumpulkan informasi sejarah jaman Singosari yang begitu lengkap mengingat ketika itu dia sedang dalam masa penahanan di Pulau Buru. Kalau jaman sekarang sih kita tinggal meng-google untuk mendapatkan kepingan info yang kita butuhkan. Tapi 3-4 dekade yang lalu? Di pulau terpencil lagi!
Saya pun jadi kurang respek dengan para penulis yang mengabaikan detail-detail cerita seperti itu. Menyebut tokohnya sebagai wartawan, tapi tak ada sedikitpun cerita yang menggambarkan dunia jurnalistik yang digelutinya (seperti cerita-cerita sinetron Indonesia yang selalu menjadikan tokoh pria utamanya sebagai eksekutif muda, tapi satu-satunya gambaran yang mengindikasikan mereka sebagai eksekutif muda adalah saat mereka menandatangani setumpuk surat-surat yang disodorkan oleh sekretarisnya). Mengambil setting Papua, tapi tak banyak sudut Papua yang bisa ia gambarkan. Atau, mengambil setting jaman perang kemerdekaan tapi menciptakan sendiri nama-nama dan peristiwanya serta pilihan tempat kejadiannya, tanpa sedikit pun merujuk pada realita sejarah yang ada. Atau kalaupun mereka mencoba menyajikan detail, hal itu dilakukan dengan kesan ‘tempelan’ yang jelas sekali. Tidak benar-benar menyatu dengan alur cerita.
Bagi saya cerita-cerita minim-riset (saat riset sebenarnya dibutuhkan) atau abai-detail seperti itu bahkan menghibur pun tidak, malah justru menjengkelkan. Kalau memang tidak ingin repot dengan riset, maka sebaiknya para penulis itu memastikan bahwa apa yang ditulisnya adalah hal-hal yang dikenalnya dengan baik. Karena, menulis idealnya adalah sebuah kegiatan transfer of knowledge atau sharing experience. Terlebih mengingat membaca umumnya dimaknai sebagai suatu aktivitas positif yang mencerdaskan bahkan tak jarang menjadi indikator kualitas hidup suatu bangsa, sehingga para generasi muda pun didorong untuk lebih suka membaca. Apa jadinya kalau kegiatan yang dianggap mencerdaskan ini hanya dipenuhi dengan sesuatu yang ‘kosong’ atau bahkan ‘menyesatkan’?
Jadi ketika dalam sebuah tulisan fungsi transfer pengetahuan atau sharing pengalaman ini diabaikan atau malah dimanipulasi, maka apa yang lebih pantas dilakukan selain menyarankan agar tulisan tersebut masuk kotak untuk diberi segel ‘un-recommended readings’?
DN