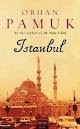Nggak kok, saya nggak salah nulis judul di atas. Lebih baik ‘nonton’ buku daripada ‘baca’ sinetron. Saya sungguh-sungguh menyarankan agar masyarakat kita, khususnya generasi muda, untuk lebih memilih mengkonsumsi buku meskipun baru pada tahap ‘menonton’ (melihat-lihat) daripada menghabiskan waktu luang dengan ‘membaca’ (menghayati) isi sinetron di depan TV. Ini merupakan ungkapan keprihatinan saya terhadap popularitas sinetron-sinetron di Indonesia yang tidak diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas, khususnya yang made in Punjabi Group. Terlalu banyak visualisasi yang tidak layak dan tidak mendidik yang disajikan kepada penonton Indonesia, dan bahkan tak jarang melecehkan intelektualitas.
Saya paham, konsumen yang dibidik para produser sinetron mungkin memang bukan kaum intelektual. Tapi bagaimana para calon intelektual yang sekarang masih duduk di bangku sekolah dan belum punya nalar yang cukup untuk menilai mutu tontonan? Sementara akses mereka terhadap TV pun tidak mudah untuk dibatasi, dan tidak semua orang tua punya waktu yang cukup untuk selalu mengawasi channel yang mereka pilih.
I’m not that extreme untuk menghimbau agar sinetron dihapuskan sama sekali dari bumi Indonesia. Kalau film-film Hollywood saja bisa menjadi industri yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan hegemoni Amerika Serikat, why not sinetron kita pada suatu saat di suatu masa menjadi hal yang sama? (minimal di kawasan-lah). Harapan saya saat ini hanyalah: jaga kualitas. Buatlah sinetron yang lebih logis, cerdas dan, syukur-syukur, bisa memberikan moral lesson (tanpa kesan menggurui). Sehingga pada akhirnya sinetron dapat dibanggakan sebagai produk Indonesia yang mewakili identitas bangsa. Dan kita pun tidak hanya terbiasa dengan slogan “Baca untuk Hidup yang Lebih Baik”, tapi juga “Sinetron untuk Hidup yang Lebih Baik” (hehehe lebay nggak sih?).
Saya tidak memaksa siapapun untuk berada pada posisi yang sama dengan saya. Saya tahu persis argumen supply and demand yang kerap dilontarkan untuk setiap keberadaan produk yang sifatnya kontroversial. Tidak ada supply tanpa adanya demand. Jadi inilah yang bisa saya lakukan untuk mencoba mengurangi demand dari sisi konsumen hiburan, khususnya TV.
Buat mereka yang telah memiliki nalar yang cukup sehingga bisa membedakan antara yang bagus dan yang jelek buat perkembangan moral, buat mereka yang merasa berpendidikan sehingga tahu persis hal-hal yang menantang dan bukannya merendahkan kecerdasan, buat mereka yang peduli untuk menjaga kualitas generasi penerus dan bangsa ini secara keseluruhan…just SAY NO TO SINETRON NGGAK MUTU and SAY YES TO KEBIASAAN MEMBACA. Peace…
(Btw, please check this out: http://pustakawan.pnri.go.id/uploads/karya/MENINGKATKAN_MINAT_BACA_MASYARAKAT.doc.)
DN