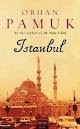Saya selalu senang baca buku-buku perjalanan. Buat saya para travellers itu adalah orang-orang dengan kehidupan yang menarik, dinamis, karena selalu menemukan pengalaman baru di banyak tempat yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda dan berbagai jenis kebudayaan yang berbeda. Akan lebih mengagumkan lagi jika mereka berhasil menaklukan berbagai tantangan yang mereka temui di perjalanan mereka dengan tabah dan berani tanpa banyak keluh kesah bahkan menjadikannya sebagai sebuah pelajaran hidup yang berharga (meski kadang saya tidak tahan untuk tidak berkomentar: “Sakit jiwa nih orang!”).
Saya selalu senang baca buku-buku perjalanan. Buat saya para travellers itu adalah orang-orang dengan kehidupan yang menarik, dinamis, karena selalu menemukan pengalaman baru di banyak tempat yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda dan berbagai jenis kebudayaan yang berbeda. Akan lebih mengagumkan lagi jika mereka berhasil menaklukan berbagai tantangan yang mereka temui di perjalanan mereka dengan tabah dan berani tanpa banyak keluh kesah bahkan menjadikannya sebagai sebuah pelajaran hidup yang berharga (meski kadang saya tidak tahan untuk tidak berkomentar: “Sakit jiwa nih orang!”).Saya kagum karena saya tahu bahwa saya tak akan pernah berani melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Membayangkan diri menjejakkan kaki di sebuah sudut dunia yang sama sekali asing seringkali tanpa teman atau bekal yang memadai, baik bekal hardware (logistik) maupun software (pengetahuan), rasanya badan saya sudah menggigil duluan. Jadi, hai para petualang, jika saja aku pakai topi maka akan kuangkat topiku untukmu...
Makanya, meskipun tampak asyik, saya tidak terkesan dengan chich and stylish travelling yang dianjurkan Amelia Masniari dalam serial Miss Jinjing-nya: “Belanja Sampai Mati di China” maupun “Belanja Sampai Mati di Jepang” (yaiyalah, wong dia melakukan perjalanan dalam rangka shopping trip...). Naik penerbangan nyaman, hotel berbintang, jamuan mewah, dan last but not least: shopping spree. Ini mah semua orang (asal punya duit) juga bisa!
Saya malah lebih terkesan dengan perjalanan backpacking mantan adik ipar Miss Jinjing, Trinity the Naked Traveller, yang oleh Miss Jinjing dibilang jenis perjalanan yang boro-boro bisa dinikmati, tapi namanya menyiksa diri. Nyari-nyari low cost airlines, penginapan murah meriah (malah kalau bisa gratis), makanan maupun transportasi lokal yang satu kriteria dengan penginapannya. Benar, perjalanan jenis ini bisa dilakukan oleh lebih banyak orang karena budget friendly, tapi saya yakin tidak banyak orang yang punya nyali seperti Trinity, mengunjungi puluhan negara asing sambil bertaruh dengan keberlangsungan hidup di sana karena minimnya dana.
Membaca kisah perjalanan para ‘petualang berani susah’ itu (kalau bilang ‘berani mati’agak lebay kayaknya) bisa sama asyiknya seperti membaca cerita fiksi fantasi, sesuatu yang sangat berjarak dari realitas hidup para pembacanya yang nyaris rutin dalam lingkaran zona nyaman. Ada pesona dunia lain yang terasa seperti negeri antah berantah, ada ketegangan saat hambatan dan persoalan muncul yang membuat kita tanpa sadar berdoa untuk keselamatan ‘sang jagoan’ maupun membenci para penghambat atau pembuat persoalan yang dimata kita jadi mirip penjahat (kadang memang beneran penjahat sih).
Sejauh ini juaranya bagi saya adalah Agustinus Wibowo. Setelah terkagum-kagum dengan petualangannya di Afganistan dalam buku ”Selimut Debu” (sudah pernah dibahas di-bog ini sebelumnya), saya kembali terpesona dengan perjalanannya di negara-negara ‘stan’yang dirangkum dalam buku “Garis Batas”. Bayangkan, Tajikistan, Kirgizstan, Kazakhstan, Uzbekishstan, dan Turkmenistan, negara-negara yang, berani taruhan, termasuk pada urutan terbawah dalam daftar negara tujuan wisata para pelancong dunia. Saya sendiri tahun 2007 hampir mendapat penugasan dari kantor untuk mengunjungi tiga diantaranya sekaligus, dan bernafas lega saat penugasan itu akhirnya dibatalkan.
Dan Agustinus seperti biasa mengunjungi negara-negara tersebut bukan sebagai wisatawan yang mengunjungi places of interest bertolak dari tempat peristirahatannya di hotel yang nyaman. Yap, sekali lagi dia berkelana seperti layaknya seorang backpacker, tapi lebih daripada backpacker, Agustinus tidak terburu-buru dalam perjalanannya, dia berusaha melebur dalam denyut nadi kehidupan masyarakat setempat walau untuk itu dia beberapa kali mengalami hal yang tidak mengenakkan.
Agustinus menamai rangkaian pengalaman travelling-nya di negara-negara ajaib itu sebagai ‘perjalanan kemanusiaan’, dan pilihan judul “Garis Batas”adalah benang merah yang menghubungkan antara kisah perjalanan yang satu dengan yang lainnya. Garis batas yang dimaksud di sini tidak hanya menyangkut isu teritorial (geografis) tapi menyangkut juga berbagai hal yang membangun identitas (kultural, etnis, politis, religis) yang memunculkan terminologi ‘kita’dan ‘mereka’.
Tapi saya tidak bermaksud untuk melulu membahas perjalanan Agustinus Wibowo di sini, mungkin lain kali. Saya lebih ingin menyampaikan apresiasi kepada para travelers yang mendedikasikan perjalanannya untuk sesuatu yang lebih dari sekedar wisata, berlibur, refreshing, atau apapun namanya yang digunakan oleh kebanyakan orang mengenai acara berpergian mereka. Kalaupun tidak didekasikan untuk alasan semulia kemanusiaan seperti Agustinus, yah at least untuk berbagi pengalaman atas sesuatu yang memang beharga untuk dibagi atau diketahui oleh orang lain,meskipun mungkin awalnya tujuannya murni pragmatis seperti kisah perjalananmencari makna cintanya Franz Wisner dalam buku “Honeymoon with My Brother”dan “How the World Makes Love” yang merupakan pelariannya setelah gagal menikah dengan sang pacar (eh, kalau dipikir-pikir, mirip tema perjalanannya Elizabeth Gilbert dalam “Eat, Pray and Love” ya?).
Buku kisah perjalanan unik lain yang pernah saya baca adalah “Around the World in 80 Dinners” atau perjalanan kulinernya suami-istri ahli masak Cheryl dan Bill Jamison di 10 negara: Indonesia (Bali), Australia, Kaledonia Baru, Singapura, Thailand, India, China, Afsel, Prancis dan Brasil. Ini asyik, bukan golongan petualang berani susah, tapi juga tidak sok berkelas seperti Miss Jinjing. Pasangan Jamison mungkin kadang harus berhemat di satu sisi (seringnya di aspek akomodasi), tapi kalau untuk urusan makan mereka benar-benar konsisten dengan tema perjalanannya: mencicipi kuliner setempat yang terbaik! Benar-benar petualangan yang membuat iri...
Oke, ada perjalanan belanja yang chich and stylist (Miss Jinjing), perjalanan jujur apa adanya alias naked travelling (Trinity), perjalanan kemanusiaan (Agustinus Wibowo), perjalanan mencari arti cinta (Franz Wisner), perjalanan kuliner (the Jamisons). Saya sendiri sudah melakukan perjalanan ke lebih dari 10 negara di hampir semua benua kecuali Afrika, dan kalau harus menamai rangkaian travelling saya dengan satu tema, maka saya akan menyebutnya.....perjalanan dinas! Hehehe, lha wong kunjungan saya ke berbagai negara tersebut adalah dalam rangka dinas kok (meskipun beberapa diantaranya saya kunjungi lagi bersama keluarga untuk vacation). Jadi kunjungan saya ke negara-negara tersebut utamanya ya untuk kerja. Kalau ada waktu atau dana lebih baru bisa diselingi acara field-trip, shopping (kebanyakan untuk oleh-oleh), atau wisata kuliner (kalau tidak terlalu banyak isu halal-haram).
Hmmh ada yang bisa di-share nggak ya? Yah, kalau harus menuliskan perjalanan-perjalanan saya tersebut ke dalam sebuah buku, pengalaman atau pelajaran yang akan saya coba sharing ke para pembaca adalah bagaimana melakukan sebuah perjalanan yang membawa misi merah-putih (baca: negara), bernegosiasi atau berdiplomasi dengan berbagai macam karakter bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di panggung internasional! Halah...
Eh, lagian kalaupun ada buku perjalanan seperti itu, siapa juga yang mau baca? :)
DN